Metode Qiyas: Analogi Hukum Islam dan Prinsip Penerapannya
TATSQIF ONLINE – Ketika masyarakat Muslim berkembang dan menghadapi tantangan sosial, ekonomi, serta budaya yang baru, muncul berbagai persoalan hukum yang belum pernah secara eksplisit dijelaskan oleh al-Qur’an maupun hadis. Dalam konteks inilah, para ulama dan fuqaha menggunakan kemampuan rasional mereka untuk menemukan hukum dari sumber utama syariat melalui metode analogi yang disebut qiyās.
Secara epistemologis, qiyās adalah upaya penalaran logis yang bertujuan menautkan antara dua peristiwa hukum yang berbeda, di mana salah satunya telah memiliki ketetapan nash dan yang lain belum. Dengan demikian, qiyās menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem ijtihad untuk menjaga agar hukum Islam tetap adaptif terhadap perkembangan zaman.
Imam al-Syafi‘i, sebagai pelopor mazhab Syafi‘i, menegaskan bahwa ijtihad dan qiyās adalah dua istilah yang memiliki makna yang sama, karena keduanya sama-sama merupakan proses berpikir hukum yang bersandar pada teks wahyu (Darmawati, 2019). Dalam sistem metodologi hukum Islam, qiyās menempati posisi keempat setelah al-Qur’an, hadis, dan ijmak, menunjukkan kedudukannya yang tinggi dalam membangun keotentikan dan dinamika fikih.
Pengertian Qiyās
Secara etimologis, qiyās berasal dari kata قَاسَ – يَقِيسُ – قِيَاسًا yang berarti “mengukur” atau “menyamakan sesuatu dengan yang lain”. Dengan demikian, makna dasarnya adalah proses perbandingan antara dua hal yang memiliki kesamaan sifat tertentu (Bahrudin, 2019).
Sedangkan secara terminologis, menurut para ulama ushul fikih, qiyās adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang belum ada nashnya dengan hukum kejadian lain yang ada nashnya karena adanya kesamaan illat atau alasan hukumnya (Ramli, 2021).
Al-Ghazali dalam al-Mustashfā menjelaskan:
“Qiyās adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan atau meniadakan hukum karena adanya kesamaan (‘illat) di antara keduanya.”
Sebagai contoh, larangan meminum khamr disebutkan secara jelas dalam al-Qur’an. Allah ﷻ berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan undian panah adalah najis termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Mā’idah [5]: 90).
Illat pengharaman khamr adalah sifat memabukkan (iskār). Dengan demikian, setiap zat yang menimbulkan efek memabukkan, seperti narkotika atau alkohol berat, termasuk ke dalam kategori yang sama dan haram hukumnya berdasarkan prinsip qiyās (Zainuddin, 2020).
Landasan Hukum Qiyās
1. Al-Qur’an
Dalil utama yang menjadi dasar legitimasi qiyās terdapat dalam firman Allah ﷻ:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir.” (QS. An-Nisā’ [4]: 59).
Ayat ini memberikan prinsip bahwa semua persoalan hukum harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bila tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks, maka proses pengembalian tersebut dilakukan melalui penalaran rasional yang berlandaskan ‘illat hukum yang terdapat dalam nash. Dengan demikian, qiyās menjadi salah satu cara untuk “mengembalikan” perkara baru kepada Allah dan Rasul-Nya melalui pemahaman sebab-sebab hukum yang telah ditetapkan (Fuad, 2016).
Dalil lain terdapat dalam QS. Al-Ḥasyr [59]: 2:
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ
Artinya: “Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang berpikir.”
Kata fa‘tabirū berarti “buatlah perbandingan”, yang menunjukkan dasar metodologis penggunaan analogi atau perumpamaan dalam hukum Islam (Bahrudin, 2019).
2. Hadis Nabi ﷺ
Rasulullah ﷺ juga memberikan legitimasi terhadap penggunaan ijtihad rasional dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, ketika beliau mengutus Mu‘adz bin Jabal ke Yaman:
بِمَ تَقْضِي؟ قَالَ: بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو
Artinya: “Dengan apa engkau memutuskan perkara?” tanya Rasulullah kepada Mu‘adz. Ia menjawab, “Dengan Kitab Allah.” Rasul bertanya lagi, “Jika tidak engkau temukan?” Ia menjawab, “Dengan Sunnah Rasul.” Rasul bertanya, “Jika tidak juga engkau temukan?” Ia menjawab, “Aku berijtihad dengan pendapatku.” Maka Rasul menepuk dadanya dan bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya sesuai dengan keridhaan-Nya.”
Hadis ini menunjukkan bahwa penggunaan akal untuk menetapkan hukum — termasuk melalui qiyās — adalah bagian dari metode ijtihad yang diakui syariat.
Kedudukan Qiyās dalam Hukum Islam
Para ulama menempatkan qiyās sebagai hujjah syar‘iyyah keempat setelah al-Qur’an, hadis, dan ijmak. Kedudukannya sangat penting dalam memastikan fleksibilitas hukum Islam terhadap perubahan zaman. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, qiyās merupakan “roh dari ijtihad” karena melalui proses ini syariat mampu menjawab problem-problem baru tanpa keluar dari nilai-nilai dasarnya (Fuad, 2016).
Selain itu, qiyās juga menjadi wujud keadilan dan rasionalitas syariat, karena hukum yang dihasilkan tidak hanya bersumber pada teks, tetapi juga pada makna dan tujuan moral di baliknya (maqāṣid al-syarī‘ah).
Macam-Macam Qiyās
Dari segi kekuatan ‘illat, para ulama membagi qiyās menjadi tiga macam (Ramli, 2021):
1. Qiyās Awlā (lebih utama)
Yaitu qiyās di mana ‘illat pada kasus baru (far‘) lebih kuat daripada pada kasus asal (aṣl). Contoh: larangan berkata “ah” kepada orang tua (QS. Al-Isrā’ [17]: 23) menunjukkan keharaman memukul atau menyakiti mereka secara fisik.
2. Qiyās Musāwī (setara)
Yaitu qiyās di mana ‘illat pada far‘ setara dengan aṣl. Contohnya larangan memakan harta anak yatim:
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api ke dalam perutnya.” (QS. Al-Nisā’ [4]: 10).
Dengan ‘illat yang sama, membakar atau menyia-nyiakan harta anak yatim termasuk dalam perbuatan haram.
3. Qiyās Adnā (lebih rendah)
Yaitu qiyās di mana ‘illat pada far‘ lebih lemah daripada aṣl. Contoh: ketika Rasulullah ﷺ membolehkan seseorang menghajikan ibunya yang telah meninggal dunia karena nazar, dengan analogi pembayaran utang. Nabi bersabda: “Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki utang lalu engkau bayar, apakah utang itu lunas?” Ia menjawab, “Ya.” Rasulullah bersabda, “Maka hajikanlah ibumu.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Prinsip Dasar dan Rukun Qiyās
Menurut jumhur ulama, rukun qiyās ada empat:
1. Al-Aṣl (الأصل) – Kasus asal yang menjadi acuan hukum.
Harus memiliki dasar hukum yang tetap dan bersumber dari nash syar‘i.
2. Al-Far‘ (الفرع) – Kasus baru yang hendak dicari hukumnya.
Harus memiliki kesamaan ‘illat dengan aṣl dan tidak terdapat nash yang menetapkannya secara langsung.
3. Hukm al-Aṣl (حكم الأصل) – hukum yang terdapat pada aṣl, yang akan diterapkan pada far‘ bila ditemukan kesamaan ‘illat.
Harus berupa hukum yang ma‘qūl al-ma‘na, dapat dicerna akal, bukan ibadah yang bersifat tauqīfī.
4. Al-‘Illah (العلة) – sebab hukum yang menjadi titik penghubung antara aṣl dan far‘.
‘Illat harus jelas, tetap, logis, serta memiliki hubungan langsung dengan kemaslahatan hukum.
Al-Ghazali menyebut ‘illat sebagai “jantung qiyās”, karena melalui penemuan ‘illat, seorang mujtahid mampu memahami makna hukum syariat secara mendalam dan tidak hanya berhenti pada teks lahiriah.
Nilai Filosofis Qiyās
Secara filosofis, qiyās mencerminkan keseimbangan antara wahyu dan akal. Wahyu menjadi dasar normatif, sementara akal berfungsi sebagai alat interpretatif yang menyingkap makna di balik teks. Dengan demikian, qiyās menjaga keberlangsungan hukum Islam agar tetap hidup, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Dalam konteks kontemporer, qiyās dapat digunakan untuk merumuskan hukum terkait perkembangan teknologi modern, seperti transaksi digital, rekayasa genetika, dan bioetika, selama ditemukan kesamaan ‘illat dengan hukum-hukum yang ada.
Kesimpulan
Qiyās adalah metode istinbāṭ hukum yang menghubungkan kasus baru dengan kasus yang memiliki nash berdasarkan kesamaan ‘illat. Landasannya bersumber dari al-Qur’an (QS. An-Nisā’ [4]: 59; QS. Al-Ḥasyr [59]: 2) dan hadis sahih tentang ijtihad Mu‘adz bin Jabal.
Rukun-rukun qiyās — aṣl, far‘, hukm al-aṣl, dan ‘illat — merupakan fondasi utama yang menentukan sah tidaknya proses analogi hukum. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, qiyās tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga sarana intelektual yang menunjukkan kebijaksanaan Islam dalam memadukan wahyu dan rasionalitas untuk mencapai kemaslahatan umat. Wallahu’alam.
Nur Aisyah (Mahasiswa Prodi PAI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)
Daftar Pustaka
Ahmad Fuad, Masfuful. (2016). Qiyās sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭ al-Ḥukm. Mazāhib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 17.
Bahrudin, Moh. (2019). Ilmu Ushul Fiqh. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja.
Darmawati. (2019). Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group.
Ramli. (2021). Ushul Fiqh. Yogyakarta: Nuta Media.
Zainuddin, Muhammad. (2020). Ijma’ dan Qiyās sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari‘ah dan Hukum, 6.

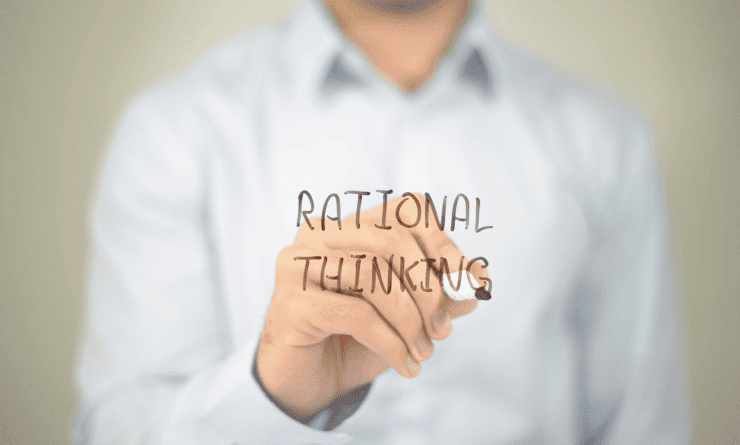

Apa contoh penerapan qiyas dalam masalah muamalah modern (seperti transaksi digital)?
Bagaimana qiyas menjaga hubungan antara hukum Islam dengan perkembangan zaman?
Bagaimana qiyas diterapkan untuk memecahkan masalah kontemporer yang tidak ada nashnya?